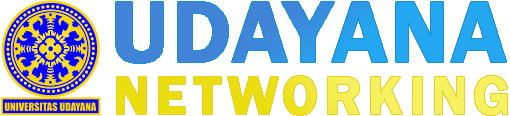Menata Undang-Undang dengan Omnibus Law
07/12/2017 Views : 518
Jimmy Z. Usfunan
MENATA UNDANG-UNDANG DENGAN OMNIBUS LAW
Oleh
Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH
(Opini ini dipublikasikan oleh hukumonline.com, tanggal 7/12/2017)
Keluhan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu perihal banyaknya undang-undang akhirnya menambah keruwetan pekerjaan pemerintah, bahkan memperlambat kinerja dalam mewujudkan pembangunan perekonomian negara. Patut dicarikan jalan keluar bersama.
Secara faktual, pemerintah telah menempuh kebijakan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) sampai saat ini, sudah di tahap PKE ke 16. Upaya penyederhanaan regulasi (deregulasi) telah dilakukan oleh pemerintah terhadap kurang lebih 222 regulasi. Dengan pola memunculkan peraturan baru yang dirumuskan dalam rangka percepatan investasi, yang berdampak pada dicabutnya beberapa peraturan terkait. Hanya saja cakupan PKE masih terbatas pada Peraturan Pemerintah (PP) ke bawah (Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri), belum mencakup Undang-Undang.
Pola penyederhanaan regulasi ini sebenarnya menggunakan metode Omnibus Law yang telah di praktikkan di beberapa negara seperti Amerika, Canada, Suriname, Irlandia, dan lainnya. Omnibus law secara sederhana, dipahami sebagai metode penyusunan aturan, yang dalam satu peraturan terdapat beberapa materi/substansi (yang biasanya dibuat secara terpisah dalam beberapa aturan) dan ketika peraturan ini diundangkan maka akan mencabut peraturan atau materi-materi dalam peraturan lainnya yang sudah diatur. Lebih lanjut dalam Black Law Dictionary, (Black Law Dictionary, Eight Edition, Thomson West: 2004:175) mengartikan Omnibus Bill sebagai berikut: A single bill containing various distinct matters. Drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. (Suatu undang-undang yang berisikan beragam materi, yang dibentuk untuk memaksa eksekutif menerima semua ketentuan yang tidak terkait atau untuk memveto ketentuan utama)
Secara implementasi, Omnibus Law yang sudah diterapkan dalam PKE ini mudah diaktualisasikan karena Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dibuat oleh kekuasaan eksekutif (dibawah kekuasaan Presiden). Berbeda halnya dengan undang-undang yang dibuat bersama DPR. Sehingga alur koordinasi lebih panjang, ditambah dengan proses tarik ulur politik.
Mungkinkah Omnibus Law dalam level UU dipraktekkan di Indonesia?
Praktek pembentukan undang-undang di Amerika dilakukan dengan cara membuat satu paket kebijakan, misalnya yang berkaitan dengan penanaman modal, maka tidak hanya mengatur soal prosedur penanaman modal, melainkan juga mengatur proses perijinan, tenaga kerja, proses pengalihan tanah, dan sebagainya. Sehingga hak dan kewajiban investor dapat ditemukan dalam satu dokumen hukum itu, dengan jumlah Pasal yang banyak.
Namun, apabila pola tersebut disadur ke Indonesia secara sama persis, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, mengingat Indonesia memiliki hirarki peraturan perundang-undangan. Sehingga 1 persoalan bisa dilihat dalam berbagai regulasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Misalnya dalam hal penanaman modal, maka akan bersentuhan dengan UU 13/2003 Ketenagakerjaan, UU 5/1960 Agraria, UU 23/2014 Pemda, UU Pajak, belum lagi Peraturan-Peraturan Daerah yang terkait.
Mengingat jangka waktu dibuatnya regulasi terkait itu berbeda-beda, maka sudut pandang pemikiran filosofis dan sosiologi dari masing-masing undang-undang dan peraturan daerah terkait juga berbeda. Hal ini akan berdampak pada potensi yang besar pertentangan diantara undang-undang tersebut. Inilah yang menjadi kesulitan bila menggunakan metode omnibus law tanpa batas. Contohnya paradigma UU Penanaman Modal lebih pada peningkatan investasi sebanyak-banyaknya dengan memberikan kemudahan kepada investor (perhatikan Dasar Menimbang huruf c dan d Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Sedangkan UU Ketenagakerjaan, kepada perlindungan hak-hak tenaga kerja (lihat Dasar Menimbang huruf c dan d, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Kemudian regulasi di bidang perijinan lebih pada perlindungan lingkungan, UU Pemda memberikan keleluasaan ke Daerah untuk mempertimbangkan kondisi di wilayahnya masing-masing.
Memang secara praktek pola ini belum pernah digunakan di Indonesia. Kendati demikian, bisa saja pembentuk undang-undang kedepan membuat UU Omnibus seperti ini. Hanya saja, UU Omnibus ini lebih mengedepankan penggunaan asas lex posterior derogate legi priori (aturan yang baru mengenyampingkan aturan sebelumnya) dengan diikuti pengaturan dalam “ketentuan penutup” untuk membatalkan undang-undang yang hendak dibatalkan. Akan tetapi, UU Omnibus ini akan menghilangkan keberlakuan asas lex spesialis derogate legi generalis (aturan yang khusus mengenyampingkan yang umum), karena UU Omnibus ini dapat dikatakan mengatur lebih umum.
Disamping itu, yang perlu dipertimbangkan dalam membentuk UU Omnibus adalah jangan sampai undang-undang baru dibuat hanya semata-mata pada satu sudut pandang, misalnya dalam peningkatan investasi saja tanpa mempertimbangkan perlindungan lingkungan, hak-hak tenaga kerja, kondisi daerah, aspek-aspek lainnya sebagai pertimbangan filosofi dari undang-undang yang akan terkena dampak pencabutan nantinya.
Tidak hanya itu, akan berbahaya juga nantinya, jika UU Omnibus ini mengandung banyak kepentingan, sehingga rawan disalahgunakan. Mengingat kedashyatannya yang akan melululantahkan bangunan-bangunan nilai-nilai keadilan dari UU sebelumnya. Sebagaimana pengalaman yang terjadi di Amerika maupun di Canada dalam beberapa dekade silam.
Omnibus Law Terbatas ala Indonesia
Berbeda halnya ketika menggunakan metode Omnibus Law terbatas, yang sebenarnya secara praktek sudah dilakukan. Salah satu pola pembentukan undang-undang yaitu menggabungkan 2 atau 3 bahkan lebih materi muatan yang diatur dalam UUD NRI 1945. Misalnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Adapun, penggabungan substansi yang diatur masih tergolong dalam 1 tema besar (terbatas).
Bahkan kehadiran UU Pemda, berdampak pada 4 undang-undang yang sudah ada sebelumnya, (mencabut 2 UU yakni UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah, dan UU No. 32/2004 tentang Pemda) serta mencabut beberapa ketentuan dalam UU MD3 dan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Begitu pula Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencabut 6 Ordonansi dan 9 undang-undang.
Pola Omnibus Law terbatas ini, merupakan mekanisme yang jauh lebih aman dan sangat dimungkinkan secara praktek. Mengingat dalam kelembagaan eksekutif, terbagi menjadi beberapa kementerian yang masing-masing telah memiliki tugas dan fungsi berdasarkan bidang-bidangnya. Begitu juga di DPR yang telah terbagi menjadi beberapa komisi. Dengan adanya Omnibus terbatas maka memudahkan penentuan kementerian yang menjadi leader dalam pembentukan undang-undang, begitu pula penentuan komisi di DPR yang menangani. Ketimbang, membentuk UU Omnibus yang tidak terbatas.
Melalui pembentukan undang-undang dengan pembatasan paradigma dalam 1 tema besar, akan memudahkan pengaturan nantinya. Misalnya UU 32/2004 tentang Pemda lebih menekankan pada otonomi yang sangat luas kepada Kabupaten/Kota sedangkan UU 23/2014 tentang Pemda menarik sebagian otonomi itu ke Provinsi. Sehingga semua ketentuan akan di dasarkan pada paradigma baru tersebut.
Untuk itu, sebaiknya Pemerintah dan DPR perlu mengoptimalkan penggunaan metode Omnibus Law terbatas ala Indonesia dengan mulai menyusun program legislasi nasional berdasarkan tema-tema, sembari juga merevisi undang-undang yang sudah lama, guna menyesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini. Tentunya, dengan tetap mempertimbangan nilai-nilai keadilan pada saat undang-undang itu dibuat.
Penulis, Pengajar HTN Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.